Tajam! Pengamat Kritik Sistem Pendidikan dan Penonaktifan Guru di Banten
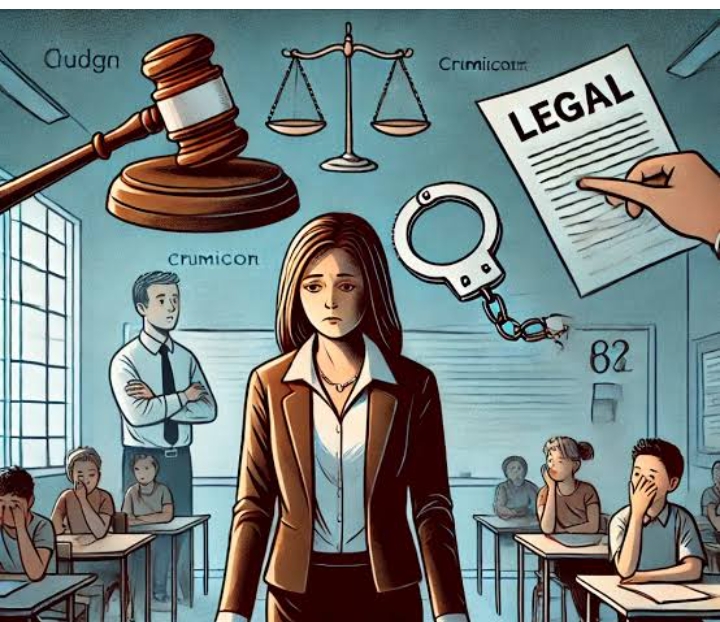
SERANG, TirtaNews – Dalam beberapa kesempatan wawancara dengan media dan forum publik, Eko Supriatno, akademisi kritis sekaligus pengamat dari Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten, menyampaikan pandangan tajam terkait dinamika moral dan kebijakan dalam dunia pendidikan Indonesia.
Salah satu isu yang menjadi sorotan ialah polemik penonaktifan kepala sekolah yang menampar siswa karena merokok—kasus yang mencerminkan benturan antara disiplin pendidikan, etika profesi, dan kebijakan birokratis di lapangan.
Menurut Eko, peristiwa ini bukan sekadar persoalan tindakan individual, melainkan cermin dari krisis sistemik dalam pengelolaan pendidikan yang semakin kehilangan arah nilai dan keteladanan.
Eko menekankan, Gubernur Banten cepat menindak dengan penonaktifan, namun kurang memperhitungkan konteks tindakan kepala sekolah.
Menurutnya, teguran atau disiplin siswa yang merokok merupakan bagian dari tanggung jawab moral pendidik, dan proses administratif yang dijalankan tanpa memahami niat pendidikan dapat mereduksi wibawa guru dan moral sekolah.
“Kepala sekolah menjalankan fungsi membimbing dan menegur siswa yang melanggar disiplin. Peristiwa ‘menepuk kepala siswa’ seharusnya dipandang dalam kerangka pendidikan, bukan langsung kriminalisasi. Guru berperan sebagai benteng karakter anak, bukan sekadar pelaksana aturan administratif,” ujar Eko.
Ia juga menyoroti proses birokrasi panjang dan ambigu di Dinas Pendidikan dan BKD, yang menurutnya memperlihatkan sistem lambat dan berlapis. “Transparansi dan keadilan proses penonaktifan seharusnya menjadi prioritas agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik,” tambahnya.
Kasus ini, kata Eko, memunculkan pro-kontra internal di kalangan guru, menunjukkan bahwa tindakan disiplin guru sering dianggap kontroversial meski niatnya mulia. Fenomena ini, menurutnya, mencerminkan kurangnya kesepahaman nilai pendidikan kolektif di masyarakat modern.
Lebih jauh, Eko menyoroti paradoks perlindungan guru vs hak individu, di mana guru dihukum karena menegur siswa, mencerminkan benturan nilai kolektif lama (disiplin, hormat) dengan nilai individual modern (hak anak, proteksi orang tua). “Standar ganda ini menunjukkan masyarakat modern lebih memprioritaskan kepentingan pribadi daripada nilai moral bersama,” jelasnya.
Dalam pandangan Eko, guru tetap menjadi benteng moral dan profesionalisme, meski menghadapi ancaman hukum, tekanan sosial, dan tantangan kesejahteraan. Kasus seperti Kepsek SMAN 1 Cimarga Dinonaktifkan Usai Diduga menunjukkan bahwa guru menjadi korban sistem hukum dan persepsi publik yang tidak selaras dengan nilai pendidikan.
Ia menegaskan, regulasi atau SOP kaku tidak dapat menggantikan pemahaman moral dan budaya pendidikan. Penegakan hukum tanpa konteks pendidikan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi guru sekaligus merusak wibawa institusi pendidikan. Perlindungan guru harus sejalan dengan keadilan, UU Guru dan Dosen, serta prinsip humanis.
Eko mengingatkan pentingnya nilai tradisional dan filosofi pendidikan, termasuk ajaran pesantren (Ta’limul Muta’allim) dan filosofi Ki Hajar Dewantara (Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani). Pendidikan efektif, menurutnya, terjadi jika nilai-nilai ini dihidupkan, bukan hanya ditegakkan melalui hukum formal.
Selain itu, peran orang tua dan masyarakat juga harus seimbang. Orang tua modern yang emosional, memprioritaskan gengsi, proteksi anak, dan hak individu menciptakan paradoks: guru berada di sisi benar tapi tetap dirugikan, sedangkan anak kehilangan pembelajaran karakter. Eko menekankan perlunya sosialisasi dan pendidikan nilai agar semua pihak memahami peran dan batas tanggung jawab masing-masing.
Dalam kritik satirnya terhadap sistem pendidikan modern, Eko menyindir, “Sekolah dan guru kerap dipandang sebagai ‘penyedia layanan’ yang harus memuaskan konsumen alih-alih institusi moral. Ketika guru menegur, ia dianggap kriminal; ketika diam, ia dituduh lalai — ironi sistem hukum dan sosial modern.” Fenomena ini, menurutnya, memperlihatkan kegagalan budaya kolektif: moralitas guru tergerus oleh hak-hak individual dan budaya instan.
Sebagai solusi, Eko menekankan pentingnya pendekatan kultural dan filosofis. Pendidikan bukan sekadar regulasi, tapi proyek budaya dan peradaban, yang nilai, falsafah, dan tradisinya harus dijunjung tinggi, dibiasakan, dan hidup di masyarakat. Semua pihak — guru, orang tua, tokoh agama, filsuf, pembuat kebijakan — perlu bersinergi membangun kesadaran kolektif.
Kesimpulannya, guru tetap berada di pihak benar; namun sistem, hukum, dan budaya modern sering membuat mereka terpojok. Masyarakat dan negara harus menghidupkan kembali nilai kolektif pendidikan: disiplin, adab, dan moralitas. Perlindungan guru adalah kunci membangun generasi yang beradab, bukan sekadar penegakan hukum formal. (Az/Red)






